Masjid yang Ramai di Hari Besar, Sepi di Hari Biasa: Sebuah Otokritik untuk Pengurus DKM
Oleh: Yamani, S.S., M.Pd.
Pengurus PC DMI Balikpapan Kota | Dosen Universitas Mulia
Balikpapan, 8 Februari 2026—Di banyak sudut Kota Balikpapan, kubah-kubah masjid menjulang anggun, pengeras suara lantang mengumandangkan adzan lima kali sehari, dan spanduk peringatan hari besar Islam berganti saban musim hijriah. Namun di balik semarak itu, sebuah pertanyaan mendesak mengetuk nurani kita: apakah masjid sungguh telah menjadi pusat kehidupan umat, ataukah hanya sesekali menjadi panggung seremonial keagamaan?
Fakta yang patut direnungkan bersama menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masih menempatkan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebagai poros utama aktivitas kelembagaan. Bahkan, secara struktural, dibentuk seksi khusus untuk mengurusi perayaan-perayaan tersebut. Tidak ada yang keliru dengan PHBI—ia adalah bagian dari syiar, ruang edukasi publik, sekaligus perekat sosial. Namun persoalan muncul ketika syiar direduksi menjadi seremoni, ketika kalender kegiatan masjid nyaris berhenti di lima momentum besar: Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi‘raj, Ramadhan–Idul Fitri, serta Idul Adha.
Di luar hari-hari itu, masjid kembali lengang. Rapat pengurus jarang digelar—kadang tak lebih dari lima kali setahun—seakan roda organisasi hanya berputar ketika ada spanduk yang harus dicetak dan penceramah yang harus diundang. Padahal dalam teori manajemen organisasi nirlaba berbasis komunitas, intensitas pertemuan pengelola adalah indikator vital dari kesehatan institusi. Rapat bukan sekadar forum administratif, melainkan ruang lahirnya visi, evaluasi, inovasi, dan keberanian untuk berubah.
Masjid, dalam sejarah Islam klasik, tidak pernah sesempit itu. Ia adalah pusat pendidikan, rumah musyawarah, ruang advokasi sosial, sentra ekonomi umat, dan kawah candradimuka kepemimpinan generasi muda. Di Madinah, Rasulullah ﷺ menjadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat membentuk peradaban. Dari lantainya yang sederhana lahir strategi sosial, solidaritas ekonomi, dan kader-kader umat yang tangguh secara spiritual sekaligus sosial.
Pertanyaannya kini: mengapa kita mereduksi warisan agung itu menjadi sebatas panggung perayaan tahunan?
Lebih menggetarkan lagi, alokasi dana masjid sering kali terkuras untuk kebutuhan seremonial: dekorasi, konsumsi, honor penceramah, dan panggung acara. Semua itu sah dan dibutuhkan. Tetapi menjadi ironi ketika hampir tidak tersisa anggaran—dan lebih penting lagi, gagasan—untuk program pembinaan pemuda masjid, pelatihan keterampilan hidup, kelas kepemimpinan, penguatan ekonomi jamaah, atau pendampingan keluarga yang terjerat kesulitan.
Di sudut saf belakang, mungkin ada ayah yang menunduk karena kehilangan pekerjaan. Di teras masjid, barangkali ada remaja yang mencari makna hidup tetapi tidak menemukan ruang dialog. Di perumahan sekitar, mungkin ada janda yang berjuang sendiri membiayai sekolah anaknya. Pertanyaannya kembali menghantam hati kita: apakah masjid telah hadir untuk mereka—atau hanya ramai ketika hari raya tiba?
Krisis ini bukan sekadar soal program; ia adalah krisis orientasi. Masjid yang hidup bukan diukur dari meriahnya panggung PHBI, melainkan dari ramainya shaf shalat berjamaah di hari biasa, dari wajah-wajah pemuda yang betah berdiskusi selepas Isya, dari jamaah yang merasakan bahwa masjid adalah tempat pulang—bukan hanya tempat singgah.
Pemuda, khususnya, tidak bisa dirangkul hanya dengan undangan menghadiri tabligh akbar setahun sekali. Mereka membutuhkan ruang aktualisasi, mentoring, pelatihan digital, kewirausahaan, diskusi intelektual, dan proyek sosial nyata. Tanpa itu, masjid akan terus menua bersama pengurusnya, sementara generasi penerus tumbuh di luar pagar spiritual yang seharusnya menaungi mereka.
Tulisan ini bukan gugatan dari luar, melainkan jeritan cinta dari dalam. Sebab mengkritik masjid dengan kejujuran adalah bentuk kesetiaan tertinggi terhadapnya. Kita tidak sedang kekurangan bangunan megah; kita kekurangan keberanian untuk mentransformasikan masjid menjadi pusat pemberdayaan umat.
Barangkali sudah saatnya DKM di Balikpapan—dan di kota-kota lain—berani melakukan pergeseran paradigma: dari event organizer keagamaan menjadi arsitek peradaban lokal. Dari pengelola agenda tahunan menjadi perancang masa depan jamaahnya.
Mari bertanya dengan jujur pada diri sendiri: berapa kali kita duduk bersama tahun ini untuk memikirkan bagaimana shalat berjamaah Subuh bisa penuh? Berapa jam kita habiskan untuk mendesain program kaderisasi pemuda? Berapa rupiah yang dialokasikan untuk mengangkat ekonomi jamaah yang terpuruk?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu membuat dada kita sesak, mungkin itulah tanda bahwa hati kita masih hidup.
Masjid tidak membutuhkan pengurus yang hanya pandai menata acara; ia membutuhkan penjaga ruh, perancang perubahan, dan pemimpin yang rela begadang memikirkan umatnya. Sebab suatu hari kelak, bukan spanduk PHBI yang akan ditanya di hadapan Allah, melainkan: apa yang telah kita lakukan agar rumah-Ku ini benar-benar memakmurkan hamba-hamba-Ku?
Dan semoga, dari kegelisahan ini, lahir keberanian baru—keberanian untuk menghidupkan masjid bukan hanya pada hari raya, tetapi pada setiap hari kehidupan. (YMN)
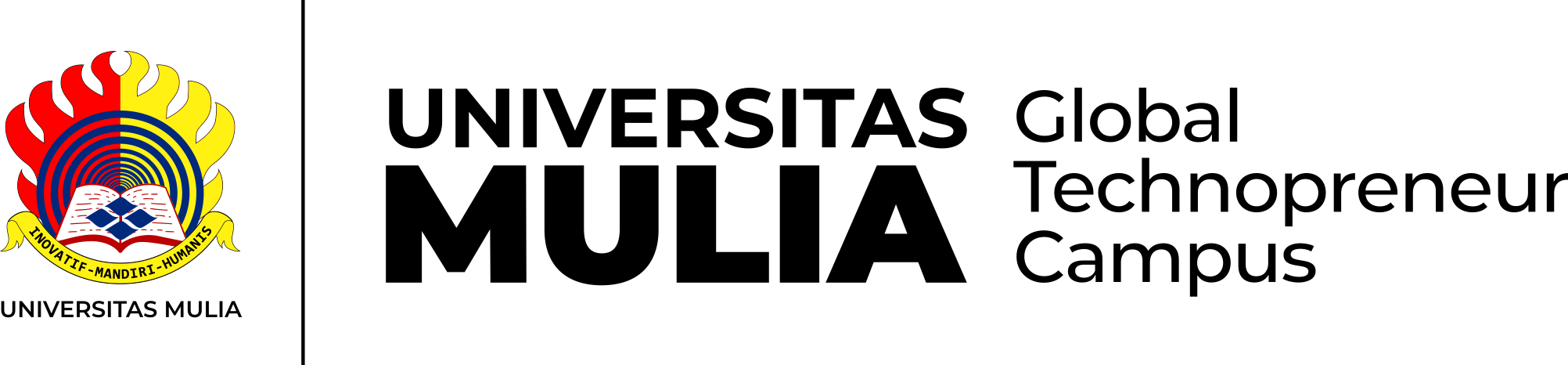








 Media Kreatif
Media Kreatif