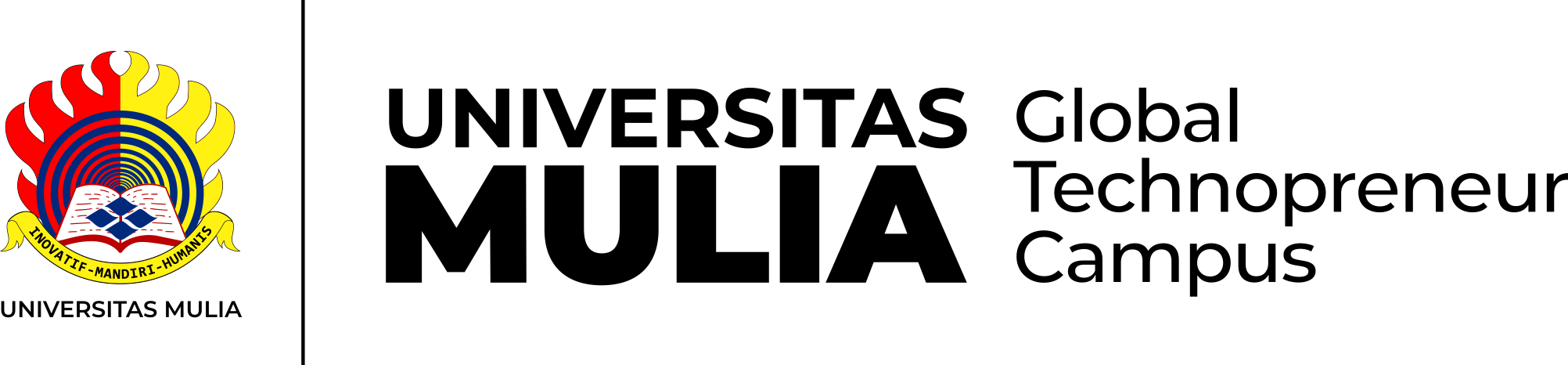Resensi Buku: Kecerdasan Buatan untuk Laut Indonesia — Peta Intelektual Konservasi Laut Berbasis Teknologi
Judul: Kecerdasan Buatan untuk Laut Indonesia: Inovasi Teknologi dalam Konservasi Ekosistem Kelautan
Penulis: Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I., dan Dr. Hadiratul Kudsiah
Editor: Dyah Ayu Noor Afifah
Desain Sampul: Syifa
Tata Letak Isi: Nara Apta
Ukuran: 14,8 x 21 cm | Halaman: xix + 480
Edisi: I (25 Juli 2025)
ISBN: 978-634-7174-77-2
Penerbit: Filosofi Indonesia Press, Yogyakarta
Laut sebagai Ruang Pengetahuan dan Data
Buku Kecerdasan Buatan untuk Laut Indonesia membuka wacana baru tentang bagaimana laut tidak hanya dilihat sebagai bentang geografis, tetapi juga sebagai ruang pengetahuan dan sumber data. Digarap oleh tiga penulis lintas bidang—Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. (Rektor Universitas Mulia), Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mulia), dan Dr. Hadiratul Kudsiah (Universitas Hasanuddin)—buku ini menggeser cara pandang konservasi dari kerja manual menjadi kerja berbasis algoritma, sensor, dan pembelajaran mesin.
Buku setebal hampir lima ratus halaman ini bukan kumpulan teori, melainkan kerangka kerja yang hidup: bagaimana ilmu kelautan, teknologi, dan kebijakan publik bisa disatukan dalam satu tujuan—menyelamatkan ekosistem laut dengan kecerdasan buatan.
Kerja Kolaboratif Lintas Disiplin
Kolaborasi tiga penulis dengan latar belakang berbeda menjadi kekuatan utama karya ini. Prof. Ahsin Rifa’i, dengan ketajaman akademiknya di bidang lingkungan dan teknologi, memetakan arah konseptual. Yusuf Wibisono menulis dengan detail teknis yang presisi, membumikan konsep AI dan big data ke dalam konteks ekosistem laut Indonesia. Sementara Dr. Hadiratul Kudsiah menghadirkan lapisan empiris dari sisi biologi kelautan dan kebijakan konservasi.
Hasilnya adalah teks yang tegas dan berimbang: sains tidak kehilangan kedalaman, dan teknologi tidak kehilangan arah moralnya.
Ekosistem Laut: Dari Biodiversitas ke Tantangan Kebijakan
Bab IV menjadi tulang punggung penjelasan ekologis. Keanekaragaman hayati laut, mulai dari terumbu karang hingga lamun dan mangrove, dipaparkan dengan pendekatan ilmiah yang ringkas dan faktual. Bab ini menegaskan bahwa laut Indonesia menyimpan modal biologis dan ekonomi yang luar biasa, namun rapuh akibat polusi, eksploitasi, dan lemahnya tata kelola.
Regulasi nasional dan internasional, serta peran masyarakat sipil, ditampilkan bukan sebagai daftar formal, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang menentukan keberhasilan konservasi.
Teknologi sebagai Instrumen Etika
Mulai Bab VI, pembaca diajak masuk ke wilayah yang jarang disentuh oleh literatur kelautan di Indonesia: penggunaan sensor, bioakustik, citra satelit, dan drone laut. Bagian ini menunjukkan bagaimana pengawasan laut dapat berpindah dari laporan manual ke sistem berbasis data waktu nyata.
Yusuf Wibisono menulis dengan pendekatan teknologis yang efisien namun tidak kering. Ia menekankan bahwa teknologi hanyalah instrumen—etika dan kesadaran ekologis manusia tetap menjadi pengendalinya.
Di titik ini, buku ini menolak glorifikasi teknologi. AI, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Ahsin Rifa’i dalam salah satu kutipan, harus “ditempatkan untuk kemaslahatan laut, bukan untuk mempercepat eksploitasinya.”
AI dan Laut sebagai Subjek Analisis
Bab VII dan VIII merupakan bagian paling kuat dari keseluruhan buku. Di sinilah kecerdasan buatan diperlakukan bukan sekadar alat bantu, melainkan subjek analisis konservasi. Algoritma diposisikan sebagai entitas yang mampu belajar dari pola ekosistem laut—mendeteksi anomali suhu, perubahan arus, mikroplastik, hingga pergerakan populasi ikan.
Pendekatan ini menandai pergeseran besar dalam paradigma konservasi Indonesia: dari konservasi berbasis pengamatan lapangan menuju konservasi berbasis prediksi dan simulasi data.
Lebih jauh, buku ini membahas integrasi AI dengan kebijakan publik, pencegahan illegal fishing, dan pembangunan ekonomi biru yang etis. Semuanya dijabarkan tanpa jargon berlebihan, menjadikan konsep yang kompleks terasa dapat diakses.
Keadilan Digital dan Ketimpangan Akses
Penulis tidak menutup mata terhadap persoalan struktural. Bab IX membedah hambatan yang sering diabaikan: infrastruktur digital yang timpang antara wilayah pesisir dan pusat kota, kesenjangan sumber daya manusia, hingga dilema etis dalam pengumpulan dan pemanfaatan data laut.
Sikap reflektif ini membuat buku ini lebih dari sekadar dokumentasi ilmiah—ia menjadi cermin sosial dan politik ilmu pengetahuan. Buku ini menegaskan bahwa tanpa keadilan digital, inovasi teknologi hanya akan memperluas ketimpangan.
Kasus dan Pembelajaran Nyata
Bab X menampilkan studi kasus, baik dari Indonesia maupun negara lain. Dari proyek pemantauan terumbu karang di Raja Ampat Papua Barat hingga penerapan drone bawah laut di Norwegia, penulis menempatkan Indonesia dalam peta global inovasi konservasi.
Kelebihan bagian ini terletak pada keseimbangan antara optimisme dan realisme. Penulis tidak memuja keberhasilan, tetapi menimbangnya dengan kejujuran akademik: bahwa setiap teknologi membawa risiko, dan setiap kemajuan memerlukan kebijakan yang matang.
Penutup
Kecerdasan Buatan untuk Laut Indonesia adalah peta intelektual tentang hubungan manusia, laut, dan teknologi. Ia menyatukan disiplin yang jarang bersinggungan dan melahirkan percakapan baru dalam dunia akademik Indonesia: bahwa laut bukan hanya ruang eksploitasi ekonomi, tetapi ruang moral, pengetahuan, dan inovasi.
Buku ini menegaskan bahwa konservasi laut masa depan tidak hanya bergantung pada niat baik manusia, melainkan pada kemampuan bangsa ini mengelola pengetahuan dan teknologi dengan nurani. (YMN)